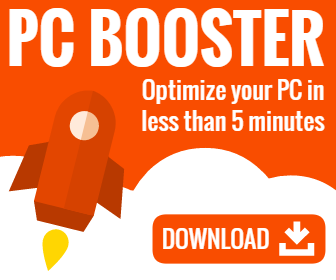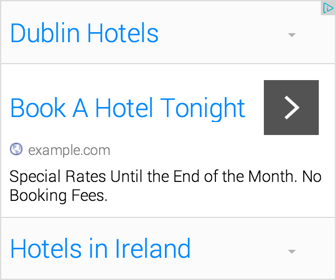Oleh Fransiskus Borgias
(Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung)
Saya memberi judul renungan kali dengan bahasa Jerman, sepenggal kalimat dari filsafat eksistensialisme Martin Heidegger, salah satu filsuf Jerman yang besar itu, pada abad keduapuluh. Judul itu sederhananya berarti bahwa hidup dan keberadaan ini adalah menuju kematian. Begitu kita mulai berada, lahir, maka secara pasti keberadaan itu terarah kepada kematian. Tidak bisa tidak. Karena itu, tidak ada cara lain bagi kita selain berusaha menerima dan berdamai dengan hal itu. Hanya dengan cara itulah kita bisa menyongsong maut itu dengan damai, baik, dan tenang. Bila perlu, dengan menimba ilham dari Santo Fransiskus Asisi, kita menyongsong maut sebagai “saudari” yang menjemput kita: Selamat datang Saudari Maut. Itu pelajaran eksistensial bagi manusia sebab suatu hari kelak kita akan mati. Tidak ada lagi fakta yang paling jelas dalam hidup manusia, selain bahwa suatu hari kelak kita akan mati dan kita tidak bisa menghindarinya. Sein zum Tode. Kepastian itu tidak bisa disangkal. Tetapi bagaimana cara kita akan mati? Itulah yang bisa dipikirkan, bahkan direncanakan. Apakah kita akan mati dengan baik? Memang itu suatu hal yang serba tidak pasti. Kita tidak bisa memastikan bagaimana dan kapan kita mati. Tetapi kita boleh mulai memikirkan, merenungkan, bahkan merencanakan untuk mati dengan baik. Bagaimana itu mati dengan baik? Itu berarti mati bagi orang lain. Yaitu membuat hidup kita menjadi bermakna bagi orang yang kita tinggalkan di belakang sesudah kita mati.
Karena itu, pertanyaan besar yang perlu kita renungan bukanlah ini, “Apa yang masih bisa saya lakukan dalam tahun-tahun tersisa dari hidup saya?” Melainkan, “Bagaimana saya bisa mempersiapkan diri menghadapi kematianku agar hidupku masih bisa bermakna bagi orang lain di tahun-tahun mendatang sesudah saya pergi?” Pertanyaan pertama, adalah pertanyaan orang yang terjepit oleh perasaan bahwa waktu sudah tinggal sedikit, waktu yang sempit. Apa yang masih bisa dilakukan dalam waktu yang sempit itu? Jika demikian, jelas hidup itu tidak bakalan bermakna apa-apa bagi sesama. Pertanyaan kedua, adalah pertanyaan orang yang sudah senantiasa sadar bahwa ada akhir suatu saat kelak, dan karena itu ia merencanakan hidupnya sedini mungkin agar bisa bermakna. Makna itu tidak harus berarti hal yang besar-besar. Makna itu juga bisa berarti suatu yang sangat sederhana, yang bisa diingat, dikenang orang. Memang hal diingat dan dikenang ini bukan lagi hak orang mati untuk menuntutnya. Jelas bukan itu. Mungkin dalam hal ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Ia mati dengan tenang di salib (itu yang dirasakan dalam injil Yohanes) karena melalui peristiwa kematian-Nya, Ia serentak mengutus Roh Cinta-Nya kepada sahabat, murid dan pengikut-Nya, yang bisa hidup dengan baik dan tenang karena penyertaan Roh Kudus itu. Yesus meninggalkan Roh Cinta. Kita pun bisa juga mengembuskan Roh Cinta itu kepada sanak keluarga dan para sahabat kita tatkala kita pergi meninggalkan mereka. Ya, hanya meninggalkan Roh atau Semangat Cinta itu.
Jika kita sudah sampai pada tingkat kesadaran itu, maka kita tidak usah lagi cemas dan gelisah mengenai waktu yang sempit dan menjepit itu, yang membuat kita seperti tergopoh-gopoh mengupayakan yang terbaik menjelang garis finis. Jika itu yang terjadi, sebenarnya hidup kita sudah tidak bermakna. Itu hanya makna yang dipaksakan. Peristiwa itu harus disiapkan dalam seluruh hidup kita. Karena itu bisa dikatakan bahwa proses atau peristiwa menyongsong datangnya Saudari Maut pun bisa menjadi sebuah karunia yang paling besar yang dapat kita persiapkan bagi diri kita sendiri dalam rangka untuk mati bahagia. Saya teringat akan ucapan Rabi Abraham Joshua Heschel bahwa ada tiga cara orang menghadapi peristiwa kematian. Pertama, ada yang meratap sejadi-jadinya. Kedua, ada yang justru diam, tidak bisa menangis, juga tidak bisa berkata-kata. Ketiga, ada yang menghadapinya dengan berpuisi. Fransiskus Asisi termasuk dalam kategori terakhir ini. Sebagai orang yang dibesarkan dalam tradisi Fransiskan, tentu saya mencoba terus berada dalam alur spiritualitas Fransiskan ini.